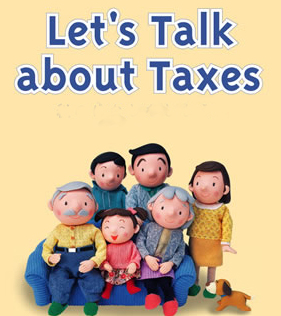Berikut ini saya sampaikan tulisan yang sedikit menyentuh saya dan saya temukan di situs www.pajak.go.id dan ditulis oleh seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak bernama Niken Pratiwi yang kalau saya ambil kesimpulan dari nama dan tulisannya adalah seorang wanita. Muda-mudahan menjadi instrospeksi bagi kita semua sebagai Wajib Pajak dan masyarakat awam yang sering menuding dengan tuduhan yang belum tentu kebenarannya dan menyamaratakan semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Tak pelak lagi boikot pajak adalah cara sangat efektif menekan kekuasaan, terutama jika dilakukan serentak oleh segenap rakyat pembayar pajak. Tidak usah boikot itu dilakukan oleh seluruh Wajib pajak, 30 persen saja terutama para wajib pajak besar, maka denyut nadi dan mesin negara bisa berhenti, dan chaos, serta gelombang anarkis tak bisa dihindari. Begitulah kalimat yang tertulis dalam artikel berjudul “Perihal Boikot Pajak” pada rubrik OPINI yang diterbitkan oleh Koran Kompas edisi Jumat, 28 September 2012. Sedih? Tidak. Karena saya tahu, “No one loves paying tax.”. Saya hanya tidak mengerti pemahaman akan boikot pajak dan apakah rakyat maupun negara mendapatkan jaminan keuntungan dari wacana seperti ini?
Rupa-rupanya, pada perkembangannya saat ini pajak tumbuh menjadi “subjek” yang harus dimusuhi –di mana pajak dianggap sebagai sebuah pemalakan dan dibayarkan dengan suasana kebatinan yang tidak mengenakkan karena konsekuensi ancaman pidana yang terdapat di dalamnya. Kemudian, baru-baru ini, muncullah wacana “Boikot Pajak” di negeri ini, akibat munculnya praktik-praktik tidak bermoral, sebut saja kolusi antara petugas dan wajib pajak yang membuat nama Gayus Tambunan menjadi fenomenal di negeri ini.
Tidak bisa dipungkiri itulah pola pikir yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya. Keterbatasan informasi maupun pengetahuan, serta bombardir pemberitaan mengenai perpajakan dari kacamata negatif dalam kurun waktu terakhir inilah yang menyebabkan munculnya stigma yang keliru seperti itu. Pajak bukan Palak. Kalau kita merasa dipalak, alangkah malunya kita pada diri sendiri, karena masih banyak di antara kita menggunakan BBM bersubsidi –di mana pajak berkontribusi cukup besar dalam pengadaan BBM bersubsidi ini. Mungkin kita sudah lupa demo besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah lantaran rencana pemerintah yang hendak menaikkan harga BBM. Sungguh serba salah. Di satu sisi, masyarakat menolak kenaikan harga BBM, namun di sisi lain masyarakat masih saja enggan membayar pajak., bahkan salah satu organisasi mewacanakan “Boikot Pajak” ke publik. Sungguh amat disayangkan, apabila masyarakat kita dibangun dengan persepsi dan pengetahuan yang keliru, yang ujung-ujungnya justru menimbulkan gerakan anarkis. Pajak seolah-olah menjadi musuh, bahkan orang-orang yang terlibat dalam institusinya menjadi di-“Gayus”-kan. Penggeneralisasian seperti ini memang tidak bisa dihindari, namun saya percaya bahwa masyarakat Indonesia masih pintar untuk tidak terjebak dalam paradigma yang salah. Tidak semua pegawai pajak berperilaku seperti Gayus. Bahkan, banyak srikandi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang harus hidup berjauhan dengan anak dan suami demi kewajibannya bekerja menghimpun penerimaan negara di pelosok negeri. Sangat disayangkan, kalau semua usaha penghimpunan pajak masih saja tertutupi oleh fenomena Gayus.
Memusuhi pajak bukanlah solusi yang bijak. Inti permasalahan adalah para pelakunya. Para pelaku pajak di sini bukanlah semata-mata pegawai Ditjen Pajak saja, tetapi juga wajib pajaknya. Sebutlah beberapa kasus yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak, terdapat andil wajib pajak juga di situ. Biasanya, para wajib pajak berharap mendapatkan keuntungan dengan membayar lebih sedikit apabila bisa bekerja sama untuk memanipulasi pajak dengan pegawai pajak. Dalam hal ini, negara yang akhirnya dirugikan. Pemasukan yang seharusnya diterima 100%, hanya didapat setengahnya, akibat praktik tersebut.
Siapakah pihak yang patut disalahkan? Mungkin kalimat inilah yang pertama muncul di benak anda, dan juga saya sebagai pegawai Ditjen Pajak. Tapi bukankah lebih baik jika kita mencari solusinya, bukan hanya terjebak dalam pertanyaan “Siapa yang patut disalahkan atas hal ini?” Apakah kalau sudah mendapat jawaban atas siapa yang salah, akan ada solusi yang lebih baik daripada sekedar wacana “Boikot Pajak”? Atau boikot pajak hanya sekedar isu yang justru hanya akan memancing provokasi timbulnya gerakan anarkis di negeri ini?
Mengutip perkataan Benjamin Franklin: “Satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah kematian dan pajak.”. Kalau pajak benar-benar akan diboikot, perekonomian di Indonesia tidak akan berjalan maksimal. Indonesia sebagai negara berkembang belum mampu membebaskan masyarakatnya dari pajak. Saya berikan benchmark dari negara-negara bebas pajak. Sebut saja Qatar yang merupakan salah satu negara terkaya di dunia, yang menggantungkan pemasukannya pada persediaan gas alam-nya. Qatar tidak mengenakan pajak pendapatan pribadi, piden, keuntungan, royalti, keuntungan modal, dan properti. Meski begitu, warga negara Qatar harus berkontribusi 5% dari pendapatan mereka untuk jaminan sosial, sementara perusahaan harus membayar 10% dana tersebut. Lain lagi dengan Bahama, sekitar 70% pemasukan negara berasal dari bea barang impor. Meski tidak ada pajak pendapatan pribadi, pegawai harus menyumbangkan 3,9% gaji mereka untuk Asuransi Nasional. Perusahaan juga harus menyumbangkan 5,9% gaji pegawai untuk program ini. Kedua negara tersebut memang dibebaskan dari pajak, tetapi sebagai gantinya masyarakat harus memberikan beberapa persen dari gajinya untuk asuransi nasional atau jaminan sosial. Hal ini masih sangat jauh dibandingkan dengan Indonesia. Walaupun Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia belum didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbaik di bidangnya untuk mengelolanya. Apalagi untuk mengganti sistem perpajakan menjadi sistem asuransi nasional. Pajak saat ini masih menjadi tumpuan pemasukan Indonesia. Kalau diboikot, apakah pembangunan harus berlangsung melalui utang? Saya pribadi saja sangat menghindari utang, saya yakin begitu juga dengan masyarakat. Masa’ untuk kepentingan negara yang toh nantinya kita juga yang menikmati, kita harus berutang –padahal kita sebenarnya mampu membayar pajak?
Saya tahu perubahanlah yang diharapkan oleh masyarakat. Begitupula saya sebagai pegawai Ditjen Pajak. Perubahan memang sedang berproses dalam tubuh Ditjen Pajak sendiri. Namun perubahan tidak akan bisa tercipta dengan sempurna apabila tidak disertai peran para wajib pajak di dalamnya. Untuk mengatasi adanya praktik-praktik yang tidak semestinya dalam perpajakan, Ditjen Pajak sudah menerapkan Whistleblowing System. Apabila masyarakat menemui hal-hal yang tidak semestinya, masyarakat bisa melaporkan hal tersebut. Dan apabila terbukti bahwa terdapat kesalahan, maka pegawai bersangkutan akan dikenakan sanksi. Tidak hanya itu, Ditjen Pajak juga bekerjasama dengan KPK untuk menindak para pegawai nakalnya.
Dari sisi internal, perubahan dalam tubuh Ditjen Pajak juga tidak akan terjadi apabila masih ditemui resistensi dari para pegawai Ditjen Pajak. Dan inilah salah satu hambatan yang masih ditemui. Tapi perlu diingat bahwa, reformasi birokrasi bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Ditjen Pajak berhadapan dengan pengelolaan 32.000 pegawai yang terletak di seluruh pelosok negeri dan tentunya ini tidak mudah. Pada satu titik tertentu, para pegawainya harus siap akan pergeseran budaya –dari budaya kerja yang berfokus pada hubungan interpersonal/kekeluargaan antara pegawainya, berubah menjadi budaya kerja profesional yang cenderung inpidual, namun tidak mengesampingkan local wisdom dan prinsip kemanusiaan. Dalam Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia 2011-2018, Ditjen Pajak ingin membangun sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dimana budaya lama seperti koneksi dan nepotisme untuk kalangan tertentu akan terabaikan, pegawai akan mulai terbiasa dengan sistem prestasi, kompetisi terbuka, dan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Diharapkan, dengan semakin transparannya sistem mutasi, promosi, dan remunerasi, Ditjen Pajak dapat menerapkan kebijakan “right man in the right place”, di mana seorang pegawai dapat menempati suatu jabatan sesuai dengan keahliannya, dan sebaliknya suatu jabatan diisi oleh pegawai yang tepat sesuai dengan standar kompetensinya. Saat inilah proses menuju arah yang lebih baik ini sedang berjalan. Kalau terdapat kasus korupsi yang mencuat dalam kurun waktu terakhir ini, justru di sinilah usaha Ditjen Pajak untuk membuktikan diri sebagai institusi yang transparan dan akuntabel. Bukankah ini yang menjadi harapan kita juga?
Sekaranglah prosesnya. Apabila proses menuju arah yang lebih baik tidak mendapat dukungan, tentunya sistem yang sudah dibuat selama 10 tahun kurun waktu Reformasi Birokrasi di tubuh Ditjen Pajak akan menjadi percuma. Saat inilah seharusnya kita bekerjasama –masyarakat dan pemerintah, agar bisa saling memberikan kontribusi yang efektif untuk pembangunan negara. Kalaupun pajak benar-benar ingin diboikot, berilah solusi yang memang efektif untuk menambah penerimaan negara. Saya sebagai pegawai Ditjen Pajak, sama halnya seperti masyarakat juga mengkritisasi dan berharap perubahan yang lebih baik dalam institusi ini. Tetapi akan lebih baik apabila kita berkontribusi melalui kritik yang memberikan solusi, bukan cuma kritik yang ujung-ujungnya memprovokasi.
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.